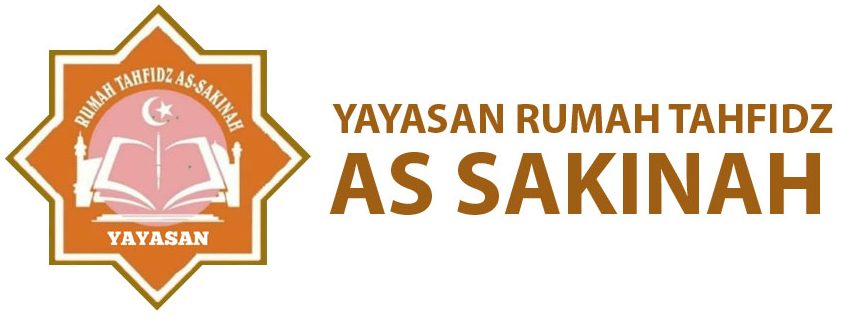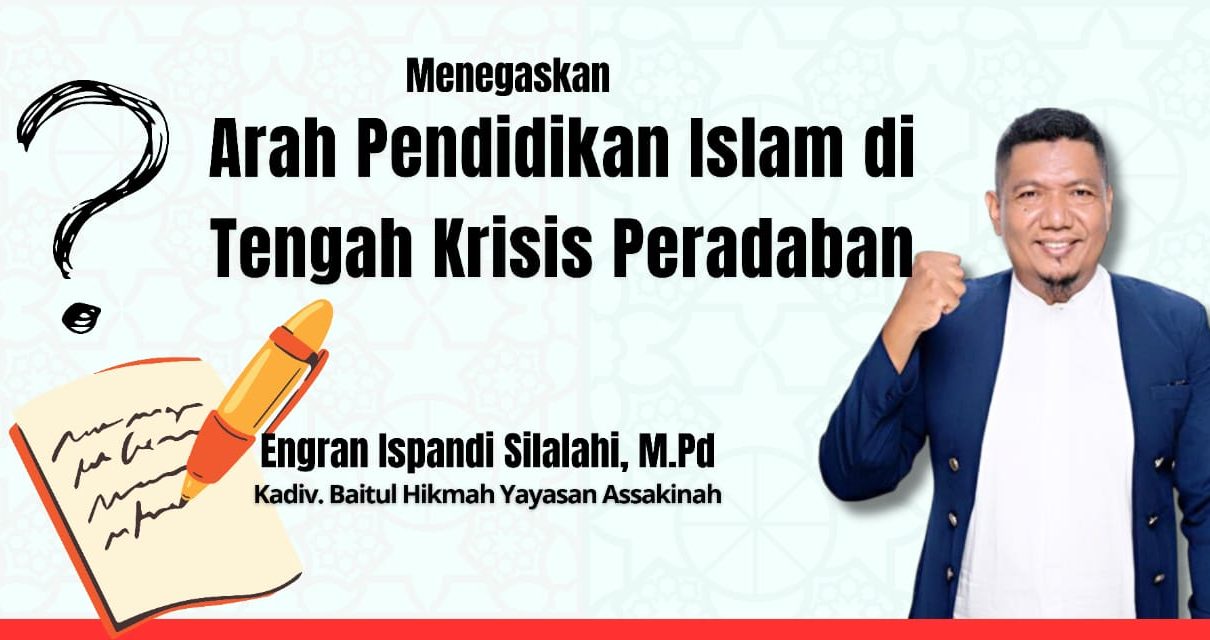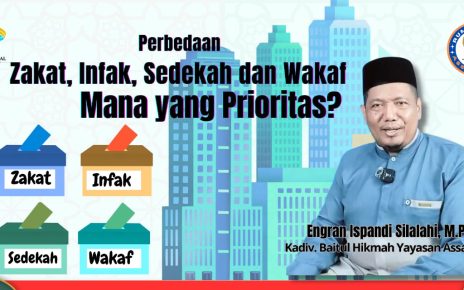Oleh: Engran Ispandi Silalahi, M.Pd.
Di tengah derasnya arus globalisasi, krisis identitas, dan disrupsi teknologi, umat Islam mengalami tantangan multidimensional yang memukul fondasi peradabannya terutama pada sektor pendidikan. Pendidikan Islam hari ini berada dalam dilema besar: apakah tetap bertahan pada tradisi pembelajaran tekstual klasik, atau melompat mengikuti irama pendidikan modern yang sekuler dan teknokratis? Di sinilah urgensinya menegaskan kembali arah pendidikan Islam, bukan sebagai upaya kosmetik kurikulum, melainkan sebagai langkah strategis rekonstruksi peradaban. Tanpa arah yang jelas dan kokoh, sekolah-sekolah Islam hanya akan menjadi replika lembaga sekuler yang dibalut simbol keislaman semata.
Krisis ini semakin dalam ketika kita menyadari bahwa banyak lembaga pendidikan Islam hari ini mengalami kekosongan visi dan kehilangan misi. Banyak sekolah berlomba pada fasilitas fisik, gelar internasional, dan status branding, tetapi gagal menjawab persoalan umat yang nyata: rendahnya literasi moral, lemahnya daya saing keilmuan, dan pudarnya adab dalam kehidupan santri. Sebagaimana dikritik Syed Naquib al-Attas, “Pendidikan sekuler telah merusak struktur jiwa manusia karena memisahkan ilmu dari adab.” Maka, jika pendidikan Islam tidak memiliki arah transformatif, ia akan menjadi “Islamisasi institusi”, bukan “Islamisasi ilmu.”
Paradoks terjadi: pendidikan Islam sering dibanggakan karena label “Qurani” namun lemah dalam tradisi berpikir ilmiah; atau sebaliknya, kuat dalam teknologi tetapi kering dari spiritualitas. Seolah umat Islam dipaksa memilih antara Alquran atau sains, antara iman atau rasionalitas. Padahal, sejak era kejayaan Islam, tidak ada dikotomi antara ilmu dunia dan ilmu akhirat. Ibn Khaldun, al-Ghazali, al-Farabi, dan Ibnu Sina adalah contoh ulama-polymath yang berhasil menyatukan agama dan ilmu. Jika hari ini pendidikan Islam tercerai-berai, itu karena kehilangan semangat integratif warisan tersebut.
Namun kita tidak bisa sekadar menyalahkan modernitas. Banyak lembaga Islam gagal melakukan kontekstualisasi pendidikan: masih terpaku pada sistem pembelajaran hafalan, berpusat pada guru, miskin metode, dan cenderung eksklusif terhadap perbedaan. Padahal masyarakat saat ini membutuhkan pendidikan yang membebaskan, membentuk kemandirian berpikir, dan memberi ruang untuk bertanya dan berdialog. Paulo Freire dalam Pedagogy of the Oppressed menekankan pentingnya pendidikan yang bersifat dialogis dan membebaskan dari belenggu penindasan struktural. Pendidikan Islam semestinya menjadi ruang pemberdayaan, bukan penjinakan umat.
Inspirasi dapat kita ambil dari sistem pondok pesantren tradisional yang membentuk karakter santri melalui pengasuhan ruhaniyah dan keilmuan yang berkesinambungan. Namun pesantren pun kini terdesak untuk beradaptasi dengan era digital. Oleh karena itu, arah pendidikan Islam ke depan bukanlah kembali ke masa lalu secara utuh, melainkan mengambil ruh keilmuan klasik dan merekonstruksinya dalam konteks kekinian. Integrasi teknologi digital dan Alquran harus dilakukan bukan dengan latah, tetapi dengan kebijaksanaan epistemik: memanfaatkan teknologi tanpa kehilangan ruh pendidikan Islam yang mendalam.
Sebagai solusi konkret, arah pendidikan Islam harus dibangun atas lima prinsip utama: (1) Tauhid sebagai dasar epistemologi, (2) Adab sebagai pilar metodologi, (3) Ilmu sebagai alat pemberdayaan, (4) Kemanusiaan sebagai tujuan praksis, dan (5) Peradaban sebagai orientasi akhir. Lima prinsip ini bukan hanya slogan, tetapi perlu dijabarkan dalam kurikulum, pelatihan guru, sistem evaluasi, hingga budaya sekolah. Pendidikan Islam tidak cukup hanya Qurani secara teks, tapi juga perlu Qurani dalam etos keilmuan dan kesadaran sosialnya.
Lembaga pendidikan Islam seperti di bawah naungan Divisi Baitul Hikmah seharusnya menjadi pelopor arah baru ini. Bukan sekadar membangun gedung atau menambah hafalan, tetapi melahirkan generasi pemikir dan penggerak umat. Kurikulum integratif, kolaborasi antara formal dan nonformal, serta sistem beasiswa berbasis keberpihakan sosial adalah jalan nyata menuju pendidikan Islam yang berpihak pada umat, bukan hanya elit. Ini bukan hanya soal sekolah unggul, tapi gerakan peradaban.
Refleksi akhir dari tulisan ini adalah bahwa pendidikan Islam harus berani bersuara dan bersikap, bukan sekadar menyesuaikan diri. Jika umat Islam ingin bangkit, maka kebangkitannya harus dimulai dari penegasan arah pendidikan, yang bersumber dari wahyu, dikuatkan oleh ilmu, dan digerakkan oleh keberanian mengambil posisi kritis di tengah gempuran nilai asing. Pendidikan yang tidak hanya menghasilkan siswa pintar, tetapi melahirkan manusia merdeka, beradab, dan bertanggung jawab pada Allah dan umat.
Penulis adalah Kadiv Baitul Hikmah Yayasan Assakinah Medan
—————————–
Daftar Pustaka:
1. Al-Attas, Syed Muhammad Naquib. Islam and Secularism. ISTAC, 1993.
2. Freire, Paulo. Pedagogy of the Oppressed. Continuum, 1970.
3. Azra, Azyumardi. Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru. Logos, 1999.
4. Al-Ghazali. Ihya’ Ulumuddin. Beirut: Dar al-Fikr, 2005.
5. Nasr, Seyyed Hossein. Knowledge and the Sacred. SUNY Press, 1989.
6. Zakiah Daradjat. Ilmu Pendidikan Islam. Bumi Aksara, 2005.
7. Abuddin Nata. Pendidikan Islam dan Tantangannya di Era Globalisasi. Prenada Media, 2015.
8. Nurcholish Madjid. Pendidikan Islam: Menjawab Tantangan Zaman. Paramadina, 2002.
9. Zarkasyi, Hamid Fahmy. Misykat: Refleksi tentang Islam, Westernisasi, dan Liberalisme. INSISTS, 2005.